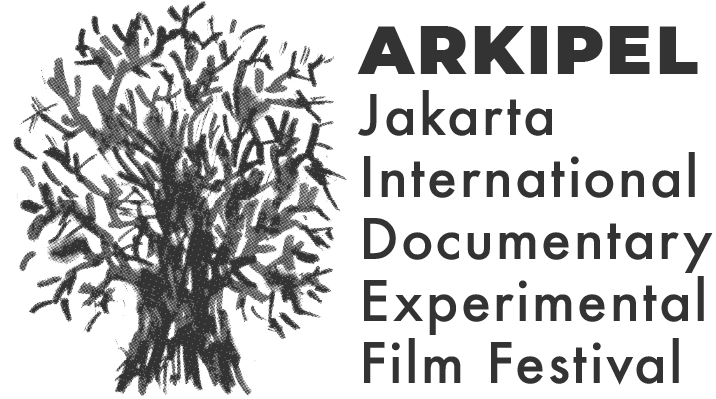28 Agustus 2013, pada Arkipel International Documentary & Experimental Film Festival 2013, dihelatkan tiga diskusi yang mempersoalkan polemik-polemik yang penting di sekitaran wacana sinema, khususnya di Indonesia. Ketiga diskusi itu berlangsung dari pukul 10.00 hingga 17:30 WIB, di Teater Kecil (Taman Ismail Marzuki), Jakarta, dan menghadirkan para pembicara yang memiliki kredibilitas karena telah berkecimpung secara mendalam pada persoalan-persoalan tersebut.
Polemik-polemik yang diperbincangkan, antara lain seputar aktivisme, sejarah dan arsip, serta kritisisme, di mana unsur-unsur tersebut turut membantu perkembangan wacana perfileman dunia. Pada masing-masing diskusi, fokus yang kemudian didiskusikan ialah bagaimana para hadirin dan hadirat diskusi bisa membaca dan menemukan gagasan-gagasan baru mengenai aktivisme, sejarah, arsip, dan kritisisme itu dalam konteks ruang lingkup wacana perfileman di Indonesia.
Diskusi yang pertama, dengan tajuk Sinema & Aktivisme, dilaksanakan pada pukul 10:00 hingga 11:30 WIB, dengan pembicara Bowo Leksono (Festival Film Purbalingga) dan Abduh Azis (Koalisi Seni Indonesia), dan dimoderatori oleh Forum Lenteng. Sebagaimana yang tercantum dalam katalog Arkipel 2013, pada diskusi ini, pembicaraan diarahkan kepada bagaimana hubungan saling-pengaruh antara tumbuh suburnya gerakan independen dan perkembangan industri perfileman di Indonesia, yang harus dilihat sebagai dua hal yang tidak harus saling bertentangan. Memang, dua ranah tersebut berjalan pada arah yang berlawanan, namun saling bertemu dan, idealnya, dapat saling menopang bagi perkembangan wacana filem itu sendiri. Khusus pada keterkaitannya dengan aktivisme, diskusi ini mencoba menarik konteks sejarah tentang loncatan perkembangan teknologi kamera sebagai alat utama produksi karya filem, mulai dari sekitaran tahun 1970, ketika para sineas menggunakan seluloid 16 mm dan 8 mm, hingga ke era pasca-Reformasi 1998, ketika semuanya dipermudah dengan adanya teknologi digital yang tersebar di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Lebih jauh, diskusi ini melihat bagaimana kelompok-kelompok inisiatif yang dengan giat mengusahakan pesebaran pengetahuan sinema guna menjembatani keterputusan distribusi pengetahuan kepada masyarakat dalam rangka membangun struktur perfilemanan nasional.
Diskusi kedua bertajuk Sinema, Sejarah & Arsip, pada pukul 13:00 hingga 14:30 WIB, dengan pembicara Intan Paramaditha, seorang penulis muda dan mahasiswi S3 yang meneliti filem untuk disertasi doktoralnya di New York University, serta dari Sahabat Sinematek. Diskusi yang dimoderatori oleh Andy Pulung (Editor Filem) ini secara umum memperbincangkan bagaimana masalah pendokumentasian filem menjadi penting dalam perkembangan filem sebagai produk budaya sebuah bangsa. Di dalam katalog Arkipel 2013 dijelaskan, khususnya di Indonesia, terdapat masalah krusial yang perlu mendapat perhatian, yakni terkait nasib pusat pengarsipan filem, Sinematek Indonesia. Oleh sebab itu, diskusi ini pun tak jauh dari perbincangan mengenai signifikansi lembaga pengarsipan dan upaya-upaya yang sudah seharusnya dilakukan untuk melestarikan sejarah sinema di Indonesia.
Sedangkan diskusi yang ketiga, pada pukul 16:00 hingga 17:30 WIB, dengan tajuk Kritik dalam Sinema, dihadiri oleh dua orang pembicara, yakni Hikmat Darmawan (pemerhati filem dan komik) dan Riri Riza (sutradara filem). Diskusi sore hari yang sempat dihadiri oleh penulis ini dipandu oleh seorang moderator, Adrian Jonathan, seorang penulis dari Cinema Poetica.
Diskusi yang ketiga ini mencoba melihat posisi kritik dan kritikus dalam perkembangan wacana perfileman di Indonesia. Mencermati perkembangan produk-produk yang mencoba menyajikan kritik mengenai filem (yang umumnya berupa tulisan), Hikmat Darmawan menyatakan pada pemaparan materinya bahwa yang menjadi PR bagi para kritikus, dan juga para pelaku filem lainnya, ialah membangun ruang atau wadah bagi terciptanya kesadaran publik, di samping upaya-upaya peningkatan kualitas dari hasil tulisan-tulisan kritik itu sendiri. “Jangan-jangan, yang jadi masalah utama dalam perkembangan kritisisme pada wacana perfileman kita adalah tidak adanya publik itu sendiri!” begitulah kira-kira kata Hikmat. Lebih jauh, Hikmat menekankan pendapatnya bahwa ekslusifitas yang selama ini terjadi di lingkungan intelektual dan para akademisi harus mulai direduksi dan mulai membuka ruang bagi keikutsertaan publik dalam mengembangkan kritik tersebut.
Sementara itu, dari sudut pandang pembuat filem, seperti Riri Riza, aktif atau tidaknya produksi karya-karya tulis kritik mengenai filem memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan kualitas produksi filem nasional. Tidak jauh beda dengan pendapat Hikmat, Riri juga berpikir bahwa perfileman kita tidak akan berkembang selama kesadaran publik terhadap kualitas filem tidak ditingkatkan. Dengan kata lain, wacana perfileman tidak hanya berpangku pada perkembangan wacana kritik, tetapi juga sejauh apa kritik itu bisa menjadi kanal apresiasi dan ruang diskusi bagi masyarakat. Tentunya, untuk memperbaiki sistem distribusi pengetahuan ini, harapan tersebsar jatuh pada kelompok-kelompok intelektual dan akademisi di lingkungan universitas. Namun, Riri dan Hikmat juga menambahkan, bahwa kekosongan inisiatif tersebut sesungguhnya dapat diatasi dengan mengamini inisiatif-inisiatif warga yang juga memiliki minat terhadap filem dan memproduksi karya-karya tulis kritik mereka melalui medium online. Oleh sebab itu, baik kritikus, pembuat filem, dan publik, harus saling menopang demi terbangunnya ilmu pengetahuan sinema yang baik dalam wacana perfileman nasional.
Pendapat kedua pembicara tersebut coba didebat oleh dua orang peserta diskusi. Penanya pertama, yang mengaku namanya Ale, berpendapat bahwa masalah yang terjadi dalam perkembangan wacana kritisisme filem di negeri ini ialah para kritikus kita tidak memiliki agenda yang jelas dalam mengembangkan wacana perfileman nasional. Dan ia menekankan bahwa seharusnya pengetahuan dasar tentang kritik itu lah seharusnya yang perlu diluruskan agar tidak melebar dan memancing salah tafsir di masyarakat.
Sementara itu, pada penanya kedua, Akbar Yumni, berpendapat bahwa yang perlu dicermati ialah perbedaan antara wacana intelektual mengenai kritik dan kritisisme, serta aksi atau gerakan populis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik. Menurutnya, dua hal tersebut tidak tepat diposisikan dalam standar ganda meskipun memang menjadi satu keharusan bagi kita untuk mendistribusikan wacana kritik filem itu ke masyarakat. “Harus diselesaikan satu per satu biar jelas,” ujarnya. Lebih jauh, yang menjadi penekanannya ialah pengetahuan tentang kritik itu yang terlebih dahulu diluruskan di lingkungan para intelektual, dan sejatinya wacana itu memang menjadi ekslusif. Sedangkan agenda populis itu lebih kepada bagaimana kita merencanakan strategi dan taktik yang jelas berbeda konteksnya dengan perdebatan-perdebatan intelektual mengenai kritik. Dengan kata lain, urutan pengembangan wacananya yang tidak bisa serta merta dapat disamaratakan begitu saja dengan sangat sederhana.
Pun perbedaan pendapat ini, satu hal yang dapat ditarik dalam diskusi yang ketiga itu ialah, pentingnya lembaga kritik dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Sebab, bagaimanapun, kritik merupakan salah satu jalan utama bagi masyarakat untuk dapat memahami apa-apa saja yang terjadi di ruang lingkup perkembangan filem nasional dan dunia, baik dari segi sejarahnya, perkembangan kontemporer, estetika, dinamika produksi, industri, maupun dalam wacana aktivismenya.