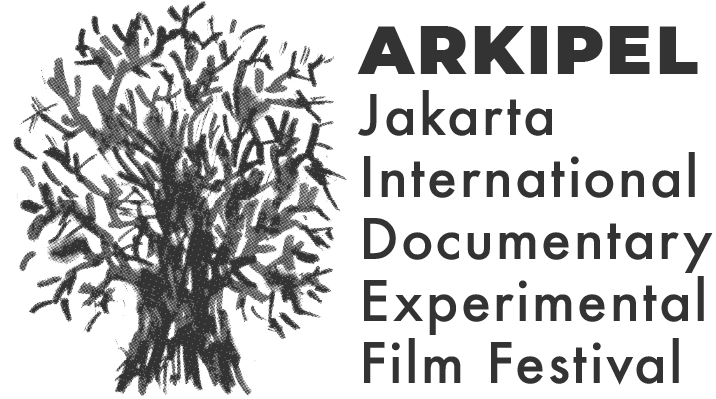Usai sudah perhelatan ARKIPEL International Documentary & Experimental Film Festival 2013 di Jakarta. Berlangsung dari 24 sampai 30 Agustus, festival bentukan Forum Lenteng ini mengadakan pemutaran film dan diskusi publik di Taman Ismail Marzuki (Kineforum DKJ dan Teater Kecil), Goethe Haus, serta Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (Sinematek Indonesia dan Usmar Ismail Hall). Total film yang diputar selama festival: 75 film dari 29 negara. Total penonton selama festival: 1004 orang.
ARKIPEL jugalah perayaan dari sepuluh tahun kiprah Forum Lenteng. Fakta ini sempat dikomunikasikan dalam pidato sambutan pada malam pembukaan festival di Goethe Haus. Dari 2003 sampai 2013, Forum Lenteng aktif berkegiatan lewat medium audiovisual melalui program-program pemutaran, diskusi, pengarsipan, kajian sosial, pemberdayaan komunitas, serta produksi film dan video.
Pada tanggal 28 Agustus 2013, redaksi Cinema Poetica mengajak Hafiz Rancajale (pendiri Forum Lenteng, direktur artistik dan juri ARKIPEL), Yuki Aditya (pegiat Forum Lenteng, direktur festival ARKIPEL), dan Intan Paramaditha (peneliti film, juri ARKIPEL) untuk duduk bersama dan bicara-bicara santai di pojok Goethe Haus. Obrolan ini diniatkan sebagai dokumentasi pemikiran yang terjadi selama persiapan dan penyelenggaraan ARKIPEL edisi pertama.
Adrian Jonathan Pasaribu: Satu narasi yang cukup lekat pada ARKIPEL adalah “Membaca fenomena global dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan budaya melalui sinema dokumenter dan eksperimental.” Niatan yang sama, kalau gue perhatikan dari kegiatan Forum Lenteng sepuluh tahun ini, sebenarnya telah diusahakan lewat program-program pemutaran macam Senin Sinema Dunia dan Doc Files, program pemberdayaan komunitas seperti Akumassa, bahkan produksi film macam Dongeng Rangkas dan Naga yang Berjalan di Atas Air. Kenapa sekarang memilih untuk mengartikulasikannya dalam bentuk festival film?
Hafiz Rancajale: Membuat festival adalah usaha untuk amplifikasi isu. Festival atau pameran besar sebenarnya kan usaha semacam itu. Kita seperti datang ke publik luas dan bilang, “Ini lho, ada persoalan.” Kegiatan-kegiatan ini mengambil isu dari berbagai sumber, baik lokal maupun internasional, lalu mengamplifikasinya di ranah publik dalam periode tertentu. Makanya ada pameran-pameran yang membawa nama bienalle (setiap dua tahun) atau trienalle (setiap tiga tahun). Ada juga yang setiap lima tahun, seperti Documenta di Jerman.
Kenapa lantas Forum Lenteng membuat festival seperti ARKIPEL ini? Ada beberapa alasan. Selama sepuluh tahun ini Forum Lenteng aktif berkegiatan lewat film dokumenter, film eksperimental, film apapun. Kami juga rajin belajar dan diskusi soal teori dan sejarah film. Isu-isu ini seringkali dianggap oleh publik sebagai isu yang terlalu elit, hanya untuk kalangan sendiri saja. Sering kan kita lihat bagaimana stigma macam ini dilengketkan pada kelompok-kelompok yang menonton dan berdiskusi film-film yang tidak biasa ditemukan di publik.
Padahal masalah sebenarnya adalah ruang. Ruangannya tidak ada. Dulu, tahun 80an misalnya, masih ada ruang-ruang untuk menonton dan diskusi film. Ada CCF [Centre Culturel Français], British Council, ruang-ruang yang memungkinkan publik untuk bertemu dengan film yang berbeda dari arus utama. Sekarang, di mana?
ARKIPEL adalah bentuk respons Forum Lenteng terhadap masalah ruang ini. Kita harus membangun ruang terbuka. Sinema bukanlah persoalan dari kami untuk kami. Ini persoalan publik, baik estetika film, budaya sinema, aktivisme, dan sebagainya. Di Indonesia, sinema baru diartikulasikan dalam tatanan-tatanan tertentu saja. Publik sering beranggapan sinema tumbuh di sekolah-sekolah film saja, atau di industri dan bioskop-bioskop saja. Padahal sinema kita tidak sesederhana itu. Di Indonesia, sinema juga tumbuh di komunitas-komunitas, di daerah-daerah, di luar kota. Sinema juga punya kehidupannya sendiri di arsip-arsip, atau di diskusi dan pertukaran ide para pengamat dan kritikus film. Publik perlu tahu soal ini, perlu terlibat dalam diskusi besar ini. Lewat ARKIPEL, kami ingin mengusahakan ruang di mana publik bisa bertemu dan berwacana soal sinema.
Selain itu, kami juga ingin menghadirkan sinema dengan penyajian yang layak. Selama ini kami nonton dan diskusi film depan perpustakaan Forum Lenteng, dengan proyektor dan tata suara seadanya. Sangat tidak ideal. Sinema dan diskusi tentangnya harus difasilitasi dengan ruang yang layak. Tadi tuh, pas film gue Anak Sabiran diputar [di Goethe Haus], gue jadi mau masuk lagi. [Tertawa]
Yuki Aditya: Kalau dari gue sendiri, menonton film itu masalah kesempatan. Sumber informasi orang dalam menonton film kan beda-beda. Ada orang yang sumber informasinya dari bioskop, jadinya kesempatan menontonnya lebih banyak di bioskop, nontonnya film-film yang beredar di bioskop saja. Gue kebetulan sumber informasinya berbeda, jadinya malah lebih banyak nonton film-film di luar bioskop. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, beda kesempatan saja.
Makanya, pas waktunya promosi ARKIPEL sama undang-undang orang buat malam pembuka, gue coba ajak teman-teman dan komunitas-komunitas yang gue tahu sedikit punya pengalaman nonton film-film beginian. Setelah pemutaran, gue ngobrol sama mereka, tanya bagaimana kesan mereka, pendapat mereka. Ini jadi masukan yang penting buat ARKIPEL, karena ini suara penonton langsung, bagian dari publik.
Obrolan awal ARKIPEL sendiri gue inget terjadi pas pertukaran koleksi. Gue cari film-film yang gue belum punya di koleksi Forum Lenteng, sebaliknya Forum Lenteng cari film-film yang mereka belum punya di koleksi gue. Terus kita bikin segambreng daftar tontonan dari pertukaran koleksi itu. Nontonlah kita tiap hari untuk beberapa minggu. Setiap habis nonton, diskusi, terus nonton lagi, terus diskusi lagi.
Dari proses ini, gue mulai sadar kalau film itu akan terasa beda dalam konteks yang beda pula. Ada gitu satu film yang tadinya gue suka banget, terus pas diskusi ngobrol sama kawan-kawan Forum Lenteng, dengar pendapat Bang Hafiz, dengar pendapat Dicky [Mahardika Yudha], kok jadi beda ya rasanya. Jadi lebih berjarak, jadi ada cara melihat yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ada film-film yang tadinya gue nggak suka, tapi jadi punya perspektif lain setelah diskusi panjang. Dari sini kemudian mulai kepikiran bagaimana ARKIPEL sebaiknya dibentuk.

Keriuhan ramah tamah festival di Goethe Haus
Adrian: Festival film, sebagaimana yang Bang Hafiz juga sudah tuturkan, pada akhirnya adalah bentuk berpolitik lewat ruang. ARKIPEL mengadakan pemutaran dan diskusi di Taman Ismail Marzuki (Kineforum dan Teater Kecil), Goethe Haus, serta Sinematek. Kenapa memilih ruang-ruang ini? Apa yang kalian baca dari ruang-ruang ini?
Hafiz: Sebenarnya kita tidak lagi punya ruang yang independen, yang diperuntukkan membaca sinema secara bebas. Bebas dalam arti tidak terbebani nilai dan kepentingan apapun. Secara historis maupun kultural, kita tidak punya ruang semacam itu. Sejujurnya gue sangat mengharapkan Taman Ismail Marzuki, tapi gue tahu dan bisa paham banyak sekali kepentingan bermain di sana, baik dari pemerintah daerah, para pelaku cabang-cabang kesenian di sana, maupun pengelolanya.
Ada satu ruang bebas nilai yang tadinya kami ingin okupasi: Bioskop Grand Theater di Senen. Kami sudah coba deal dengan yang punya, soal harga tiket, harga sewa, peralatan, dan sebagainya. Negosiasinya tidak mulus. Mereka ngotot dengan harga sekian, kami ngotot dengan harga sekian. Memang setelah kami lihat lagi, kalaupun jadi di sana, energi kami akan terkuras habis. Lo tau sendiri tempatnya bagaimana: parkirnya sedikit, lokasinya agak mojok di tikungan, dan sebagainya.
Tapi, sebagai ruang, Grand Theater Senen itu lebih cocok untuk apa yang kami niatkan dalam ARKIPEL. Secara kultural, bioskop itu punya akar yang kuat dengan tradisi menonton kita: dekat pasar, dekat keramaian, sarang prostitusi. Secara historis, bioskop-bioskop macam Grand Theater yang ada di benak penonton kita dulu. Mental penonton kita ada di situ sebenarnya, bukan di tempat macam Goethe Haus ini. Tradisi menonton kita ada di bioskop. Kalau kita nonton film yang menang ARKIPEL kemarin itu, Old Cinema, Bologna Melodrama, kerinduan yang muncul adalah kerinduan ke bioskop.
Menurut gue, kondisi perbioskopan di Indonesia itu udah klinis. Kalau gue lihat 21 sama Blitz, semuanya terasa steril; semuanya kan masuk ke dalam mall begitu. Gue mengalami sinema di sini dari tahun 80an, dari nonton di bioskop misbar [gerimis bubar] sampai akhirnya nonton di sinepleks. Awalnya, pas coba nonton di sinepleks, gue seneng. Rapi, bersih, audiovisual baik. Tapi, lama-lama, gue merasa ada yang hilang dari sinepleks-sinepleks ini: sinema sebagai geliat kultural. Sinema kan tidak cuma yang terjadi dalam bioskop, tapi juga geliat kultural di lingkungan tempat menonton. Ini yang hilang dalam sinepleks.
Jadilah, kami memilih tempat-tempat ini: Kineforum, Teater Kecil, Goethe Haus, Sinematek. Prioritas kami yang penting ada ruang dulu, ruang yang punya tradisi menontonnya sendiri, yang alternatif dari bioskop-bioskop sekarang.
Gue juga sebenarnya berharap banyak sama Kineforum. Dari dulu, kalau ngobrol dengan kawan-kawan di Dewan Kesenian Jakarta, gue selalu bilang kalau gue mau Kineforum jadi tempat yang hardcore dalam konteks tradisi sinema. Itu jadi tempat nongkrong bagi penggiat dan penikmat sinema, ada popcorn juga, ada diskusi juga. Itulah yang gue rasa bisa jadi gambaran riil dari apa yang gue sebut sinema sebagai geliat kultural.
Intan Paramaditha: Melihat kecenderungan filmgoing sekarang, bioskop-bioskop kan hampir semuanya di mall. Akibatnya, kegiatan menonton jadi bagian dari one-stop shopping. Lo ke mall, mampir ke bioskop, lihat film apa saja yang main, terus nonton deh. Jadi seringnya penonton cuma numpang lewat saja, seperti tidak ada persiapan sebelum menonton film itu sendiri. Festival, menurut gue, penting dalam konteks itu. Ia merayakan filmgoing; ia menuntut lo untuk bersiap secara kultural sebelum mengkonsumsi barang yang disebut film. Lo punya ritual dan persiapan diri sebelum nonton.
Ibaratkan kaya nonton teater. Sebelum nonton teater, orang pasti baca ulasannya dulu, atau baca naskahnya kalau memang pementasannya dari naskah yang sudah beredar luas, terus siapin pakaian, siapin pikiran, baru nonton. Menurut gue, menonton film seharusnya juga diperlakukan seperti itu.
Hafiz: Menonton film itu kaya ibadah. Sebelum sholat lo cuci muka dulu, siapin mukena, terus ibadah dengan khusyuk. Selama ibadah, lo nggak mau kan diganggu orang. Tradisi menonton film macam ini yang gue rasa udah mulai hilang di Indonesia.
Gue setuju sama Intan soal festival film merayakan filmgoing. Ada tradisi sinema yang harus dijaga. Beberapa festival film di Indonesia yang pernah gue datangin kadang lupa soal hal ini. Gue tidak bermaksud mengkritik secara negatif kawan-kawan yang selama ini sudah berjuang bikin festival. Masukan saja. Gue beberapa kali datang ke festival-festival di Indonesia, masuk ke ruang pemutaran, putar filmnya pakai DVD, terus proyektornya ada di depan penonton. Nah, hilang tuh sensasi sinema buat gue. Sinema itu bukan proyeksi di depan penonton, tapi di belakang penonton. Ruangan gelap, cuma ada film di depan, tidak ada yang menghalangi. Gue strict banget soal ini. Misalkan film-film Forum Lenteng diputar dengan tidak layak, dalam konteks pemutaran dalam gedung ya, gue pasti stop pemutarannya. Sensasi sinemanya tidak terbentuk.
Intan: Sama tuh kaya pas gue nonton The Act of Killing di manalah itu. Waktu itu sekelas wajib nonton film itu, tapi banyak cahaya dari luar masuk ke ruang pemutaran. Kami jadinya terganggu. Wah, gue harus nonton film ini lagi di tempat yang lebih layak. We have to respect the medium.
Hafiz: Nah, kalau dalam konteks menonton sebagai ibadah, lo nggak bakal tuh mikir soal angka. ARKIPEL nggak ambil pusing soal uang yang harus dikeluarin untuk bikin pemutaran yang layak, tidak terlalu kecewa kalau melihat penonton sedikit atau keluar di tengah pemutaran. Ini ibadah. Bikin pemutaran yang layak itu seperti kasih infaq ke orang-orang. [Semua tertawa]
Seperti kata Intan, kita harus respek sama mediumnya. Kita harus respek sama penonton yang sudah meluangkan waktu, harus respek juga sama orang yang jauh-jauh sudah bawa film untuk diputar di ARKIPEL.
Adrian: Ada lima juri di ARKIPEL tahun ini. Empat pegiat Forum Lenteng, satu lagi Mbak Intan. Masing-masing juri, termasuk dalam Forum Lenteng sendiri, pastilah punya gagasan sinematiknya sendiri. Gue penasaran, bagaimana kalian menyusun koridor penjurian di ARKIPEL? Apa poin-poin yang ingin ditekankan? Kualitas macam apa yang ingin kalian kedepankan?
Intan: Kalau dari yang kami sepakati bersama, penjurian di ARKIPEL mencoba mendedah konten, estetika, dan kemasan film. Yang kami cari adalah karya yang mampu menjaga proporsi antara elemen-elemen ini. Tapi, selama proses penjurian, kami menemukan karya-karya yang menonjol di satu-dua aspek saja dan tetap menginggalkan kesan tersendiri di antara kami.
Ada karya yang kontennya tidak setajam yang lain, tapi punya inovasi estetik yang segar. Ada pula karya yang secara tematik punya muatan politis yang penting, tapi pengerjaannya biasa saja. Contohnya ada satu film Mesir [A Man Since Long Time karya Mahmoud Yossry] tentang pandangan remaja di Mesir perihal ekspresi seksualitas. Aturan sosial di sana kan sangat ketat, jadinya ada friksi tersendiri nih di kalangan anak-anak muda ini. Secara politik, film ini penting. Sayangnya, ketika dihadapkan dengan karya-karya yang lain, film ini tidak dikemas dalam estetika yang inovatif.
Poin-poin yang kami ingin tekankan dalam ARKIPEL adalah bukan soal apa yang kamu ingin katakan lewat film, tapi juga bagaimana kamu mengatakannya. Ada kedalaman tersendiri di situ, ada kerumitan tersendiri yang mungkin perlu dihadirkan. Di sinilah kami coba memberi value terhadap masing-masing karya, dan juga terhadap kompetisi ini keseluruhan.
Hafiz: Sederhananya, ARKIPEL mau cari film bagus. Tapi, bagus seperti apa? Dalam diskusi di Forum Lenteng beberapa bulan sebelum ARKIPEL, kami coba bedah lagi terminologi-terminologi sinema yang kami rasa akan bergulir sepanjang ARKIPEL. Kami bedah lagi apa itu film dokumenter, apa itu film eksperimental, apa itu film fiksi, apa itu jembatan antara fiksi dan dokumenter, dan sebagainya. Kami bahas lagi semuanya dalam konteks sinema.
Pertanyaan pertama Intan waktu sesi penjurian: kenapa memisahkan dokumenter dan eksperimental? Sebenarnya tidak memisahkan, karena toh kompetisi di ARKIPEL menyatukan semua jenis film. Tidak ada pembagian jenis di dalamnya. Makanya kami diskusi panjang soal terminologi ini, supaya punya pijakan bersama saat penilaian.
Eksperimentasi yang ARKIPEL maksud itu cair sifatnya. Dalam arti, kita bisa menemukan eksperimentasi dalam film manapun. Dalam film fiksi, kita bisa lihat apakah konten film disampaikan dalam bahasa sinema yang ‘standar’ atau yang berbeda. Dalam film dokumenter juga begitu, kita bisa lihat bagaimana logika-logika kenyataan disampaikan atau malah dibolak-balik dalam medium film.
Seperti kata Intan, kami menjuri dengan tiga elemen tadi: konten, estetika, dan kemasan. Kemasan kami rasa perlu dinilai karena itu juga bagian dari penuturan sinema. Waktu mengerjakan OK Video dulu, ada istilahnya “standar broadcast”, standar minimum yang harus dipenuhi supaya suatu video bisa disiarkan di televisi. Sinema juga punya standar minimum itu.
Ada satu aspek lagi sebenarnya yang kemudian berperan dalam penjurian ARKIPEL. Kami menyebutnya personality. Masing-masing juri punya otoritasnya sendiri, masing-masing punya sejarah tontonannya sendiri. Aspek ini yang menjadikan kami semua punya penilaian yang berbeda. Film A misalnya dapat nilai empat dari gue, enam dari Ugeng [Moetidjo], beda lagi dari Otty [Widasari]. Dari sini terkumpul beberapa film yang kemudian kami bawa ke tahap berikutnya.
Intan: Sepuluh film.
Hafiz: Sepuluh film itu yang kami bawa ke tahap berikutnya: perdebatan. Ini tahap yang paling gue suka selama penjurian. Kami para juri mencoba membaca karya satu per satu, membandingkannya dengan karya-karya lain, dan menempatkannya dalam konteks estetika, sosial-politik dan sebagainya. Hasil perdebatan ini yang kami sampaikan dalam catatan juri untuk setiap film pemenang.
Adrian: Satu keunikan yang gue tangkap dari kompetisi di ARKIPEL adalah tidak ada pembedaan durasi film. Kebanyakan festival film yang gue tahu jelas pembagiannya; ada kompetisi sendiri untuk film panjang, kompetisi sendiri untuk film pendek. Di ARKIPEL pembagian itu tidak ada. Kenapa pihak ARKIPEL memutuskan untuk menggabungkan film beragam durasi ini dalam satu kompetisi? Bagaimana para juri merespons keragaman durasi ini dalam penilaian?
Hafiz: Gue pribadi tidak pernah membedakan film panjang, film pendek, video art, apapun. Buat gue itu masalah medium saja. Lo mampu nggak menangkap isu ini dalam durasi film lo? Lo mampu nggak membangkitkan imajinasi filmis dalam setengah jam, atau malah bisanya dalam dua setengah jam? Durasi film itu kan pilihan. Ada orang yang ingin bertutur dalam dua menit, ada juga yang mau bertutur dalam dua setengah jam, tapi bukan berarti yang dua menit itu lebih bodoh dari yang dua jam. Dalam penjurian, pemilihan durasi ini jadi petunjuk sendiri dari proses berpikir si pembuat karya.
Intan: Gue melihatnya seperti cerita pendek dan novel. Lo nggak bisa membandingkan keduanya karena masing-masing bentuk punya tuntutannya sendiri. Jadi cara menilai kami adalah lagi-lagi proporsi. Seberapa efektif film lo. Untuk durasi sekian, apakah film ini sudah efektif untuk gagasan yang ingin disampaikan? Karena ada saja film yang durasinya dua jam, tapi sebenarnya malah bisa diedit lagi. Ada juga film yang cuma beberapa menit tapi rasanya kok butuh durasi yang lebih. Ini masalah ketepatan wadah dan gagasan.

Suitcase of Love and Shame, karya Jane Gillooly (Amerika Serikat), salah satu film pemenang ARKIPEL 2013
Adrian: Di kompetisi ARKIPEL tahun ini ada tiga film Indonesia: Perampok Ulung karya Marjito Iskandar Tri Gunawan, Canggung karya Tunggul Banjaransari, The Flaneurs #3 karya Aryo Danusiri. Bagaimana kalian melihat film-film Indonesia ini di antara film-film dari berbagai bangsa di seksi kompetisi? Pergulatan estetika macam apa yang tiga film ini tawarkan dalam konteks estetika global?
Intan: Bagi gue, tiga film Indonesia yang masuk di ARKIPEL itu baik, terutama kalau kita bandingkan dengan kebanyakan film Indonesia yang ada sekarang ya. Kecenderungan yang sering gue temui, ini gue bicara untuk film Indonesia secara keseluruhan ya, adalah kelemahan banyak pembuat film kita memberi kerangka pada gagasan dalam karyanya. Banyak film Indonesia, yang kalau kita bikin checklist, pasti ketebak polanya. Yang paling banyak itu isu gender sama Islam. Seksi banget kan dua isu itu di film kita. [Tertawa] Pertanyaannya kemudian, bagaimana lo bisa mengkomplikasi penuturan gagasan itu?
Di sini kemudian jadi penting untuk melihat film-film yang terdahulu, baca buku, mencari referensi, mengukur sejauh mana gagasan ini sudah disampaikan. Ini pekerjaan rumah besar yang kita perlu lakukan bersama. Yang sering gue tangkap dari film-film kita adalah sikap yang menganggap gagasan yang sedang disampaikan itu terra incognita, frontier banget, revolusioner lah, tapi lupa kalau sebenarnya gagasan yang serupa sudah pernah disampaikan dengan cara yang lebih rumit, dengan cara yang lebih delicate. Kalau kita bandingkan dengan sastra, misalnya, setiap penulis punya komplikasinya sendiri dalam menyampaikan gagasannya. Tidak bisa menyampaikan gagasan begitu saja secara telanjang.
Dalam pengamatan gue terhadap sinema Indonesia sepuluh tahun terakhir ini, gue menangkap sejumlah kesegaran sebenarnya, sejumlah usaha eksperimentasi. Gue menemukan sejumlah film yang membawa kemasan yang khas. Film-film Joko Anwar, misalnya. Tapi, ada baiknya eksperimentasi ini diikuti oleh kesadaran sejarah. Kita perlu melihat lagi ke belakang, eksperimentasi macam apa yang sudah terjadi dalam medium sinema. Kita pun perlu melihat lagi ke masa sekarang, apa saja sebenarnya tantangan yang perlu direspons. What was experimental back then might not be experimental now.
Perlu juga ada kesadaran tersendiri tentang keterkaitan bahasa sinema yang digunakan dengan yang ada di Indonesia ini. Gue melihat banyak pembuat film di sini beberapa kali berusaha meminjam idiom-idiom visual ‘baru’, tapi tidak jelas apa paradigma atau pemikiran di balik itu. Kenapa lo perlu bahasa visual seperti itu? Misalkan film Wong-kar Wai. Bahasa visual yang ia bangun kan ada akarnya dengan cara pandang orang-orang Hongkong akan kotanya. Di Indonesia bagaimana?
Gue merasa banyak film-film Indonesia sekarang yang terasa seperti kolase. Gambar itu mengingatkan gue akan gambar yang mirip di film lain, gerakan kamera itu mengingatkan gue akan gerakan kamera di film lain, tapi gue tidak bisa menangkap kenapa image itu harus ada dalam film. Harus ada penggalian lebih lanjut dari paradigma di balik keberadaan image-image dalam film. Film-film Indonesia dulu bisa jadi lebih punya alasan di balik gambar-gambar yang dihadirkan. Apa yang Kau Tjari, Palupi?, misalnya, begitu ketat dalam penataan mise-en-scene karena pembuat film ingin bertutur lewat itu. Adegan di kamar Haidar [protagonis Palupi] itu kan detail banget; dari situ kita bisa tahu bagaimana sih si tokoh ini. Ada keterkaitan yang kuat antara ide dan kemasan.
Hafiz: Gue rasa tiga film itu cukup punya kelengkapan dari segi konten, estetika, maupun kemasan. Ada usaha ekspermentasi yang menarik di sana. Kami para juri mengangkap itu dan apresiatif terhadapnya. Namun, kalau kita bandingkan dengan film-film lain, gue melihat penguasaan bahasa sinemanya belum seluas kawan-kawan di luar. Kalau jadi penulis, kita kan harus punya kosa kata yang banyak, tahu tata bahasa, tahu EYD, dan sebagainya. Penguasaan yang komperhensif itu yang memungkinkan lo tahu apa batasan medium yang lagi lo pegang, dan kemungkinan eksperimentasi apa yang bisa lo jalani.
Pembuat film juga begitu. Gue ngomong begini bukan berarti film-film Indonesia di kompetisi ARKIPEL jelek. Malah sebaliknya. Karena film-film ini sudah baik, sudah cukup berimbang, gue optimis ke depannya bisa berkembang lebih lagi. Marilah kita sama-sama memantapkan dan memperluas penguasaan bahasa sinema kita.
Secara umum, baik dari pengamatan gue pribadi maupun dari teman-teman di Forum Lenteng, gue melihat ada gap yang besar soal penguasaan bahasa sinema di kalangan pembuat film kita. Gue tidak bilang tidak ada eksperimentasi di sinema Indonesia. Ada eksperimentasi tersendiri terjadi di wilayah konten, penuturan, dan sebagainya, tapi tidak banyak. Di Forum Lenteng kita sering nonton film-film Indonesia lawas. Waktu nonton film-film Wim Umboh, misalnya, kita melihat bagaimana beliau mencoba-coba banyak jenis montase untuk menuturkan ceritanya. Mengutip pernyataan JB Kristanto, Wim Umboh ini kan tidak terlalu mahir dalam menyutradarai aktor, jadilah dia bermain dengan montase. Ini bentuk eksperimentasi sendiri. Teguh Karya punya bentuk eksperimentasinya sendiri, Sjuman Djaya punya caranya sendiri, Garin Nugroho pun begitu.
Gue jujur jarang nonton film-film Indonesia sekarang. Jujur saja gue jarang. Paling kalau ada teman-teman Forum Lenteng bawa DVD film Indonesia, gue tonton terus biasanya gue matiin setelah lima belas menit. Dari lima belas menit pertama, akan terlihat eksperimentasi suatu film sampai mana, dan seringnya gue tidak menemukan itu. Tapi tidak berarti gue mengabaikan pencapaian kawan-kawan yang lain. Gue menangkap usaha eksperimentasi yang sangat asyik dalam film-film Edwin, misalnya.
Setelah banyak diskusi di Forum Lenteng dan kawan-kawan lain, ada satu jenis eksperimentasi yang tidak mungkin kita baca langsung di layar, yaitu eksperimentasi metode produksi. Kita mau memproduksi sinema, tapi karena tidak mungkin menggunakan ukuran-ukuran yang standar, jadilah kita menggunakan cara-cara lain supaya pengalaman sinematik yang diinginkan itu bisa terlaksana. Bowo Leksono dan kawan-kawan di Purbalingga bisa dibilang konsisten dan sukses melakukan ini. Kami di Forum Lenteng juga mengusahakan itu. Kalau kami buat Anak Sabiran atau Elesan Deq a Tutuq dengan standar-standar industri, kita nggak bakal mungkin bikin film.
Dalam konteks eksperimentasi metode produksi ini, jadi menarik melihat film-film Indonesia, baik yang sekarang maupun yang dulu. Gue ingat di Forum Lenteng kami pernah nonton satu film Sjuman Djaya, kalau nggak salah, terus diskusi panjang. Dalam film itu, gue lupa sekarang judulnya apa, kami menemukan banyak ‘kejutan’. Contohnya ada satu gerakan kamera yang agak canggung; kamera berusaha mengikuti satu tokoh, panning sebentar, terus zoom ekstrim. Film-film kita dulu sering banget kan begitu. [Tertawa] Kalau kita mengacu pada bahasa sinema yang ‘proper’, kan harusnya nggak begitu caranya. Tapi keputusan kreatif ini menarik, karena dilakukan dengan sadar oleh pembuat filmnya dan malah memperkaya karyanya.
‘Kejutan’ ini, setelah kami pikir-pikir lagi, bisa terjadi karena penguasaan bahasa sinema yang berbeda dalam kru. Yang sekolah film kan Sjuman Djaya saja tuh, pengarah kameranya gue yakin belajar di jalanan. Untuk menjembatani gap ini, si pengarah kamera perlu eksperimentasi dengan cara yang dia tahu dan pengalaman yang dia punya. Makanya bisa muncul ‘kejutan-kejutan’ seperti yang gue bilang tadi. Waktu itu Ugeng bilangnya ‘aspirasi lokal’. [Tertawa] Kalau film Sjuman Djaya itu dibawa dan diputar ke Rusia, mereka pasti terkaget-kaget. Kok begini jadinya? Ini beda dengan bahasa sinema yang selama ini mereka tahu. Artikulasi film Sjuman Djaya itu punya keunikannya dan kekayaannya sendiri.
Untuk film Indonesia sekarang, ini spekulasi gue ya, banyak pekerja film kita bisa dibilang sudah terdidik soal produksi film. Pembuat-pembuat film Indonesia sekarang bisa jadi sudah terlalu nyaman dengan cara produksi mereka, sehingga kemasan film-film yang mereka buat memang baik tapi hilang kejutan-kejutan kulturalnya. Keadaan sekarang jelas perlu disikapi berbeda. Gue percaya satu-satunya cara untuk memunculkan kembali kejutan-kejutan itu adalah dengan belajar lagi sebanyak-banyaknya dan cari tahu sudah sampai mana sih kita sebenarnya. Bisa kita coba nonton lagi wayang, terus lihat bagaimana ya kalau penuturan wayang kita terapkan dalam sinema kita, misalnya. Bisa kita coba kunjungi lagi sejarah film dunia, Hollywood, Uni Soviet, apalah. Gue pribadi, sebagai pembuat film, memilih untuk mempelajari teori film dan kanon-kanon sinema dunia.
Adrian: ARKIPEL sendiri gue lihat punya concern yang begitu mendalam pada kesejarahan sinema. Di program-program kuratorial, misalnya, tidak ada batasan waktu film apa saja yang bisa diputar. Gue juga lihat program Gelora Indonesia di Sinematek, yang memutar newsreel dan dokumenter lawas Indonesia yang selama ini tersimpan dalam koleksi Sinematek.
Yuki: Memang penting bagi ARKIPEL untuk mengangkat kesejarahan sinema ini. Satu hal yang ingin kami coba jelajahi dan bagi ke publik adalah bagaimana sih proses pemikiran di balik film-film zaman dulu, image-image masa lampau. Konteks apa sih yang menaungi mereka, terus bagaimana sih pengaruh latar sejarah, sosial, politik, dan sebagainya itu berpengaruh ke bahasa sinema waktu itu. Karena kami merasa image masa lalu dan masa sekarang punya kaitannya sendiri, dan itu penting untuk dipahami publik.
Pas bantu Dicky menyusun program Gelora Indonesia, misalnya, gue banyak kagetnya. Kualitas seluloidnya masih baik, bersih banget, karena kalau kata orang Sinematek film-film itu waktu itu cuma diputar sekali terus langsung masuk arsip. Nggak pernah diputar lagi. Terus, pas kami coba tonton newsreel dan dokumenter lawas itu, banyak temuan menarik. Ada satu video penyuluhan masyarakat tentang pemilu. Isu yang mau diangkat itu tata cara pemilu sama himbauan untuk menghindari sogok-menyogok. Setting filmnya itu keluarga. Ada satu ibu yang terima duit dari simpatisan partai manalah. Terus dia diwanti-wanti sama anak sama suaminya supaya balikin duit itu. Tiba-tiba videonya ganti gambar. Kita langsung lihat superimpose muka ibu itu sama jeruji penjara. Sekarang lihat begituan jadi terasa surreal gimana gitu, tapi kalau bayangin orang dulu nonton itu menjelang pemilu, kok jadi asyik ya buat kita diskusiin.
Ada juga rekaman-rekaman pidato Soekarno. Setelah nonton beberapa kali, gue sama Dicky baru sadar kalau komposisinya selalu berulang. Soekarno selalu ada di kanan frame; setiap dia nunjuk, tangannya selalu mengarah ke kiri. Itu jadi dokumentasi visual tersendiri bagaimana gejolak politik waktu itu. Terlihat juga bagaimana budaya visual kita waktu itu berakar dengan lingkungan sekitarnya.
Hafiz: Satu catatan yang perlu disampaikan juga adalah katalog ARKIPEL. Faktanya, festival ini sangat murah. Uang paling banyak dihabiskan untuk sewa proyektor dan bikin katalog tebal itu. Untuk sewa proyektornya, jelas alasannya, soal kelayakan suasana menonton yang tadi kita obrolin itu. Untuk katalog yang tebal itu, kami merasa perlu untuk mencatat tidak saja film-film yang diputar dalam ARKIPEL, tapi juga kenapa film-film itu yang dipilih untuk ditayangkan. Ini penting untuk rujukan di masa mendatang, baik bagi keberlanjutan kami sebagai penyelenggara festival maupun publik sebagai pengunjung festival dan penikmat sinema.
Adrian: Forum Lenteng sudah sepuluh tahun aktif berkegiatan sebagai komunitas. Sementara itu, dari pengamatan gue, komunitas adalah salah satu bentuk yang lazim kita temui dalam skena perfilman kita, tapi sedikit sekali komunitas film di Indonesia yang bertahan lebih dari dua tahun. Masalahnya biasanya dua: habis duit atau habis ide, kadang kombinasi keduanya. Gue lebih penasaran sama perkara gagasan. Bagaimana Forum Lenteng menjaga konsistensi pergulatan ide dalam komunitas kalian sehingga bisa bertahan selama sepuluh tahun ini?
Hafiz: Kalau istilah gue, yang biasanya ditertawakan kawan-kawan yang lain, kita harus selalu gelisah. [Semua tertawa] Maksudnya, lo harus terus membangun kegelisahan dalam diri lo sendiri, dalam tubuh komunitas lo. Kegelisahannya soal apa yang kalian percayai. Misalkan komunitas produksi film. Lo udah bikin satu film, diputar di mana-mana, diomongin banyak orang, sukses, terus berhenti. Habis kegelisahannya.
Kawan-kawan Forum Lenteng, baik secara komunitas baik secara individu, selalu mengusahakan supaya kita tidak nyaman terus-terusan. Harus ada kondisi tidak stabil yang menantang kita untuk terus bergerak. Karena, bisa jadi, setelah kita bergerak itu ada kesempatan lain yang terbuka.
Yuki nih, contohnya, gue cemplungin. [Yuki tertawa] Tadinya dia hidup stabil, kerja dari siang sampai malam, berpenghasilan, nonton banyak film. Buat gue, sia-sia saja kalau pengetahuan film dia yang ribuan itu cuma buat dirinya sendiri. Gue jadikan dia direktur festival; Yuki jadinya ada di kondisi tenggelam, muncul, tenggelam, muncul. Gue merasa, dengan bergulat semacam itu, hidup jadi punya arti. Yuki harus berenang supaya sampai ke tujuannya. Nggak gampang, tapi buktinya jadi tuh ARKIPEL edisi pertama. Sepuluh tahun lagi, dengan bekal pengalaman ini, bisa saja kan Yuki jadi direktur festival di Belanda, misalnya.
Forum Lenteng sendiri tidak pernah mengarahkan anggota-anggotanya untuk menekuni profesi tertentu. Dalam arti, kami tidak pernah memaksa semua anggota Forum Lenteng harus jadi filmmaker, misalnya. Itu terserah pilihan masing-masing orang, mau jadi filmmaker, mau jadi kurator, mau jadi jurnalis, terserah. Apapun pilihannya, kami bersama-sama siap menyumbangkan modal-modal pengetahuan, tapi lo harus siap juga kalau ada tantangan yang muncul karena lo menekuni pilihan lo.
Makanya, kalau lo lihat lagi film-film panjang yang Forum Lenteng udah produksi, dari Anak Sabiran sampai Naga yang Berjalan di Atas Air sampai yang paling baru ini Elesan Deq a Tutuq, semuanya nggak ada yang dapat funding. Kadang suka heran kalau di forum-forum, suka ada pendapat “Forum Lenteng mah enak dapat funding terus.” Kita bikin film itu dengan duit sendiri, hasil tabungan sendiri. Kalaupun ada nama Ford Foundation di kredit titel, itu adalah ucapan terimakasih karena mereka sering mendampingi kami.
Proyek Dongeng Rangkas, misalnya, nilainya cuma empat puluh juta. Duit itu juga kebanyakan dipakai untuk workshop kawan-kawan di Rangkasbitung, untuk anak-anak Forum Lenteng tinggal di sana selama sebulan. Baru deh kami dan kawan-kawan di sana coba bagaimanapun caranya Dongeng Rangkas jadi. Atau misalnya Elesan Deq a Tutuq. Gue bilang ke kawan-kawan yang bakal berangkat ke Lombok, “Ini ada duit segini. Pokoknya pulang harus jadi satu feature film.” Ini kan bikin orang gelisah, tapi juga jadi tantangan bagi mereka. Mereka bakal punya feature film pertama nih, tinggal bagaimana mereka memenuhi tantangan itu. Setelah itu, gue yakin, bakal terbuka kesempatan-kesempatan lain bagi mereka. Begitu cara kami bertahan selama sepuluh tahun ini.
Telah ditulis oleh Adrian Jonathan di Cinema Poetica pada 3 September 2013.